Suatu hari di Asrama Puteri
Gadis di pinggir tempat tidur yang sedang menggaruk-garuk kepalanya itu mengumpat dalam hati. Seharusnya ia sudah curiga saat melihat Honda City silver yang mangkrak di pelataran parkir kampusnya beberapa hari yang lalu.
Sayang waktu itu ia terlalu sibuk dengan urusan praktikumnya. Coba kalau tidak, mungkin ia sudah mendatangi iblis itu dan mencegah segalanya terjadi.
Tapi kenyataannya, seperti biasa, Dita selalu terlambat datang.
Sekarang, ia terpaksa mendengarkan ratapan dari salah seorang sahabat terbaiknya-yang tidak mengikuti perkuliahan sejak tiga hari lalu.
Kamar dimana ia berada sekarang mulai terasa kecil dan panas.
Dita meraih gelas air putih di atas meja.
Matanya memandang sedih pada gadis yang kemudian meraih gelas di tangannya. Wajah gadis yang kesehariannya tampak cerah itu sudah terlalu pucat untuk menyimpan sari-sari kehidupan.
Mirip sosok mayat hidup.
Tubuhnya sepintas terlihat jauh lebih kurus daripada biasanya. Rambutnya awut-awutan.
"Sudahlah, Ros.. Hanya masalah cowok," bisiknya, seraya mengusapkan jemari tangannya di rambut sahabatnya. Gadis di atas tempat tidur meletakkan gelas kembali di atas meja, lalu memejamkan mata.
Setitik lagi air mata jatuh ke atas bantal.
"Segalanya begitu sempurna, Dit," isak Rosa. Bahunya berguncang.
"Aku tahu. Ia pasti membuatmu bahagia saat itu. Jauh lebih bahagia dari semua yang pernah kaurasakan. Ia membuatmu jatuh bangun, kan?"
Rosa menganggukkan matanya, masih terpejam.
Dita menarik nafasnya dalam.
Jangan pernah ada yang mengatakan bahwa ia tak mengerti akan semua itu. Walaupun Rosa tidak menceritakan seratus persen tentang segalanya, Dita sudah bisa menebak apa yang terjadi.
Baginya, sosok iblis itu bukanlah seorang yang asing.
Ia sangat mengenalnya.
Salah seorang lagi dari sekian banyak sahabat.
Semula Dita tak mengerti, siapa yang membuat Rosa jadi berantakan, dan bagaimana caranya.
Setahu Dita, Rosa memiliki banyak sekali teman pria.
Tapi tak seorangpun yang dinilainya mampu membuat gadis itu terluka.
Rosa bukanlah tipe gadis yang mudah untuk dipermainkan. Sampai Rosa menyebutkan nama seorang pemuda yang membuatnya tersentak.
Dio? Dio yang itu?
Dio yang membantai wanita dan gadis kecil tanpa berkedip?
Hancur sudah!
Dita menunggu sampai sahabatnya tertidur. Ia meraba kening gadis itu, mendapatinya sedikit hangat.
Alis Dita berkerut.
Pemuda itu benar-benar keterlaluan.
Dita mungkin masih merasa tak mengapa, seandainya pemuda itu menyelesaikan apa yang sudah ia mulai-membuat gadis itu terluka tanpa menyisakan sekeping cinta lagi.
Tapi dengan menarik harapan terindah dari seorang wanita di tengah jalan saja, sudah merupakan sebuah siksaan lahir batin.
Apalagi dengan membuat si gadis tetap merasa yakin, bahwa pemuda itu tak bersalah. Dalam jangka waktu yang panjang, Dita yakin, Rosa akan tetap menyimpan harapan itu di hatinya.
Harapan kosong, tentang kembalinya sang pemuda.
Menyedihkan sekali.
"Ia pergi karena ia menyayangiku. Aku bisa melihat kesedihannya," begitu isak Rosa yang sempat didengarnya belasan menit lalu.
Dalam hati Dita mencibir.
Mana mungkin?
Satu-satunya alasan atas kejadian itu yang bisa diterima nalarnya, adalah pemuda brengsek itu sudah membuat si gadis sedemikian rupa, meletakkannya dalam batas yang ia inginkan, agar supaya ia bisa melepaskan diri dengan mudah, dengan rasa cinta yang semakin membara di hati si gadis.
Dita meninggalkan kamar Rosa dengan merenung.
Antara kekagumannya, rasa benci, dan ingatan akan luka panjang di punggungnya, Dita meringis tanpa ia sadari di dalam mobil.
Iblis-iblis ini luar biasa.
Ia menyukai pemuda itu, di luar sifat buruknya-karena pemuda itu adalah seorang sahabat yang baik.
Dio memang baik, tapi hanya dengan orang yang dianggapnya sahabat.
Selain itu, ia akan jahat seperti binatang buas.
Dita mengerti, karena pemuda itu suka menceritakan segala sesuatu padanya.
Gadis itu berani bertaruh, janji makan siang kali ini, pasti merupakan kedok belaka. Ia sudah bisa membayangkan wajah pemuda itu, dengan cengiran khasnya, menceritakan tentang segala apa yang dialaminya sebulan sejak pertemuan mereka yang terakhir di warung batagor.
Saat ia hendak berlalu, sebuah bayangan melintas di samping mobil.
Dita melirik ke arah spion. Dengan heran ia memandang dua sosok yang turun dari motor hitam.
Adegan selanjutnya mirip sinetron India.
Si gadis menghentakkan kaki, menutupi wajahnya, terisak masuk ke dalam Asrama puteri.
Sementara sosok pemuda berambut panjang di samping motor hitam hanya berdiri. Lalu memutar tubuh.
Gadis di dalam mobil bisa melihat wajahnya dengan jelas.
Dita tercekat.
Tio? Si manusia beku? Iblis yang lain?
Pemuda itu berhenti memandang ke arahnya. Dari spion, Dita melihat pemuda itu tersenyum.
Jari telunjuk pemuda itu menempel di pelipisnya, untuk kemudian menunjuk ke depan. Tanpa mengatakan apapun, pemuda itu menaiki motor hitamnya, lalu melaju ke arah yang berlawanan dengan arah mobil Dita menghadap.
Dita terpana sejenak.
Otaknya bekerja.
Sembilan puluh sembilan persen ia sudah menebak apa yang telah terjadi.
Tapi semoga dugaannya salah. Satu persen saja.
Dita menemukan kedua makhluk itu di cofee shop biasanya-tempat ia pertama kali mengenal Dio setahun lalu, dan Tio sebulan setelahnya.
Kedua makhluk itu tampak bahagia.
Senyum dan cengiran di wajah mereka, diselingi tawa.
Dita melangkah pelan-pelan menghampiri. Alisnya berkerut, jelas gadis itu tampak gusar.
Belum terlalu dekat, salah seorang dari kedua pemuda itu sudah melihatnya.
"Dit!" Dio berseru seraya melambaikan tangan.
Tio menoleh dan tersenyum.
Dita tidak membalas sapaan dan senyuman yang dilontarkan kedua orang itu. Langkahnya semakin kaku saat ia mendekat.
Gadis itu berhenti di samping meja oval.
Matanya memandangi kedua pemuda itu satu-satu, tajam, tak ada yang luput.
"Duduk dulu, duduk dulu," Tio berkata seraya menarik kursi.
"Aku tidak mau duduk," ucap Dita ketus.
"Ayolah," tawa Dio, menepuk meja.
"Tidak," sahut Dita, "tidak sebelum Tio menceritakan tentang akhirnya."
Dio dan Tio berpandangan, lalu tertawa berbarengan.
Dita melihat Tio menoleh, menatapnya dengan senyum jelek.
"Tidak ada apa-apa. Hanya bilang `putus, yuk?’ Itu saja." Gadis di samping meja menatap wajah pemuda yang baru saja berkata dengan tajam.
"Hanya itu?" tanya gadis itu lagi.
Tio mengangguk, mengiyakan.
Dalam hati Dita mengeluh, pemuda ini tak kalah jahatnya. Malah terang-terangan. Segampang itukah meninggalkan gadis yang tengah jatuh cinta baginya?
Dita tak mengenal Tio sebaik ia mengenal Dio. Tapi ia tahu betul, mereka serupa. Dita berpaling ke arah Dio.
"Lalu, kenapa sahabatku Rosa?"
"Mana aku tahu," sahut Dio menunjukkan tampang bodoh.
Dita menarik kedua tangannya ke samping, berkecak pinggang menatap dua orang sahabatnya yang benar-benar unblelieveable.
"Kalian benar-benar deh," ucapnya beberapa saat kemudian. Dengan gerakan cepat Dita menurunkan tas punggungnya, lalu mengayunkannya ke lengan kedua pemuda itu. Masing-masing satu. Kedua pemuda itu tak menghindar, malah tertawa terbahak-bahak. Dita lalu mendudukan tubuhnya di kursi yang sudah ditarik.
Wajahnya masih kerut merut. Bagaimanapun, ia merasa sebal di hatinya.
"Dit," Dio berbisik, "mau Banana Ice?"
Dita melebarkan matanya.
"Wah? Mau dong!"
Ketiga sahabat itu lalu bersepakat melupakan apa yang sudah terjadi. Mereka bertiga memang demikian, cepat sebal satu dengan lainnya. Namun cepat juga mencairkan kebekuan dengan canda tawa.
Walaupun dalam hati Dita merasa kasihan pada Rosa dan Shinta, sebagai sesama wanita, tapi Dita tahu-yang ada dihadapannya saat ini, adalah dua sahabat terbaiknya, bukan iblis yang mengerikan.
Ia tak bisa mengubah hal itu.
Ia hanya bisa bertekad, lain kali akan berusaha lebih keras untuk menghalangi kejadian-kejadian serupa terulang kembali.
"Tapi, Dit. Menurutmu, jahat mana aku sama Tio?" mendadak Dio bertanya.
Dita menelan potongan pisang sebelum menggeleng, "Entahlah. Bagiku kalian semua sama brengseknya.
Nggak ada bedanya selain warna kulit. Itu juga kalau gelap ngga kelihatan."
Dio saling pandang dengan Tio, lalu sama-sama menunjuk.
Nyaris pula berbarengan saat berseru, "Kamu yang kalah!"
Dita menyaksikan mereka berdua dengan bingung.
"Ada apa sih sebetulnya? Kalian taruhan, ya? Brengsek deh!"
Tio terkekeh, mengetuk ujung rokoknya di asbak.
"Ini hanya masalah...."
Dio menyahut,"Bayar hutang!"
“Yup, di Angkringan Biru”, Tio melanjutkan.
Dita bengong.
Epilog
Deadline Day
satu setengah jam kemudian.
Angkringan Biru.
Semua orang mendengarkan dengan nafas tertahan. Satu setengah jam mereka seolah terbuai....tak berkata-kata.
Tio menghembuskan asap dari bibirnya.
"Akhir cerita," lanjut Dio, "tak ada yang menang."
Setelah Dio mengatakan demikian, terdengar suara mesin mobil mendekat. Sebuah Jazz kelabu berhenti di dekat warung.
Tio mengangkat tubuhnya, meraih jaket di sudut meja warung. Matanya bergerak ke samping.
Dio tersenyum.
"Ya," bisiknya lagi, sambil tersenyum, menatap semua orang yang ada di dalam warung, "tak ada yang menang."
Menyambar kotak Marlboro-nya, Dio menyusul Tio yang sudah keluar warung. Jendela mobil bergerak turun, wajah tersenyum seorang gadis terlihat.
Sesaat kemudian, warung itu terasa sepi.
"Lhah, kalau tak ada yang menang..."
"Hutangnya...," mbah meneruskan.
Orang-orang yang ada di warung saling pandang.
Lalu nyaris serentak mereka semua tertawa.
Semuanya merasa baru bangun dari sebuah mimpi.
Tukang ngamen, yang baru pertama kali singgah di Angkringan Biru, mengambil sepotong tempe, lalu bertanya, "Siapa sih mereka, mbah?"
Mbah Wono, dengan tersenyum, menggeleng-gelengkan kepala.
"Bukan siapa-siapa. Hanya dua orang tukang hutang yang suka mendongeng."
[TAMAT]
----------Bermain Api Atau Api yang Bermain? (CHAPTER 9-FINAL END)-----------------
 Yang Nulis Si
Yang Nulis Si








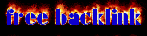


0 komentar
Posting Komentar
Silahkan berkomentar apa saja yang terkait pada artikel ini. Terima Kasih.